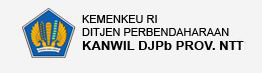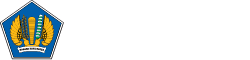Seberapa Jauh PAD, TKD, dan KUR Berpengaruh Pada Kesejahteraan Masyarakat?
Opini : Totok Wijanarko, Kepala Seksi PSAPP
Tahun 2023 Indonesia genap berusia 78 tahun. Di usia yang hampir delapan dekade sejak proklamasi, Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Data BPS tahun 2022 mencatat, 26,36 juta rakyat Indonesia masuk kategori miskin. Kondisi serupa terjadi pula di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tahun 2023, NTT masuk dalam tiga provinsi paling belum sejahtera di nusantara (CNN Indonesia, 2023).
Guna mengatasi permasalahan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan UU tersebut, pemerintah kabupaten/kota (pemda) memperoleh kewenangan lebih besar dalam memungut pajak dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Disamping itu, pemerintah pusat juga berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dengan membuka akses permodalan usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak diinisiasi tahun 2007, masyarakat lebih mudah mengakses sumber pembiayaan. Sasaran KUR adalah UMKM dengan nilai usaha yang feasible namun tidak bankable karena terkendala kolateral. Dengan KUR, diharapkan UMKM semakin mampu meningkatkan struktur modal dan memperluas lapangan kerja.
Keterkaitan dana transfer, PAD, KUR, dan hasil pembangunan menjadi topik pembahasan para peneliti. Todaro & Smith (2012) menggunakan GDP dengan faktor purchasing power parity sebagai indikator pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi dilakukan melalui kebijakan fiskal bertalian erat dengan PDRB (Suliswanto, 2010; Maulida & Zuhroh, 2017). Dengan indikator GDP per kapita, Perkembangan infrastruktur keuangan berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (Beck et al., 2007).
Studi terkait isu-isu tersebut tidak menunjukkan hasil yang konklusif. Begitupun, analisis hubungan antar variabel belum memasukkan peran variabel mediator. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian: (1) apakah PAD, TKD, dan KUR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi NTT? (2) apakah PAD, TKD, dan KUR berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dengan mediasi PDRB? dan (3) apakah PAD, TKD, dan KUR berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NTT dengan mediasi PDRB?
Tinjauan literatur Praktik desentralisasi fiskal dapat ditinjau dari kerangka teori fiscal federalism (Puspita & Hamidi, 2021). Tiga tokoh utama menjadi pelopor dalam konsep fiscal federalism yaitu Kenneth Arrow, Richard Musgrave, dan Paul Samuelson yang berkontribusi di dalam literatur keuangan publik era 1950-an dan 1960-an (Oates, 2005). Teori ini berangkat dari pandangan bahwa ketika sistem pasar gagal dalam menjalankan fungsi penyediaan barang publik, pemerintah akan hadir dengan kebijakan untuk mengoreksinya.
Asumsinya, institusi pemerintahan adalah pengampu kepentingan publik yang berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat dengan motivasi demi pengabdian atau karena adanya tekanan dari voters. Pemerintah yang gagal memenuhi ekspektasi rakyat akan mendapat sanksi berupa kehilangan suara (kalah) dalam pemilihan umum. Konsep pemikiran tersebut tercatat sebagai the first-generation theory of fiscal federalism (FGT).
Asumsi di dalam FGT berlaku dalam konteks sistem pemerintahan yang berjenjang (desentralisasi). Pemda berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat daerah. Masyarakat akan diuntungkan karena punya banyak pilihan barang publik yang disediakan pemda yang bersaing memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mana hal itu tidak didapatkan jika barang/jasa disediakan oleh pemerintah pusat (Tiebout, 1956).
The second-generation theory of fiscal federalism (SGT) dikembangkan untuk melengkapi FGT pada era 1960-an dan 1970-an oleh Richard Musgrave dan Wallace E. Oates (Puspita & Hamidi, 2021).
Pemikiran yang berkembang adalah desentralisasi memungkinkan antar pemda saling bersaing. Iklim kompetisi mendorong pemda berlomba untuk meningkatkan perekonomian setempat. Singkatnya, persaingan menciptakan insentif pemda untuk menetapkan kebijakan yang memajukan perekonomian daerah. Kompetisi yang efektif perlu pembatasan anggaran yang ketat yang berkaitan dengan pinjaman dan transfer dana antar daerah (Weingast, 2009).
SGT menekankan aspek kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri (PAD). Pemda yang mampu menggali PAD dianggap lebih akuntabel. Ini dilatarbelakangi pandangan bahwa dana transfer dari pusat kebanya-kan dipakai untuk menutup defisit anggaran daerah, dimana daerah punya kecenderungan memperlebar defisit tersebut. Maka SGT menekankan perlunya membuat sistem transfer dengan memperhatikan prestasi/capaian kinerja pemda dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
Sumber Data dan Model Penelitian Penelitian ini mengambil sampel kabupaten/kota di provinsi NTT sebanyak 22 kabupaten/kota. Data TKD dan PAD diambil dari Laporan Government Finance Statistics (GFS) tahun 2018 s.d. 2022 Audited. Data KUR didapat dari Treasury Big Data. Adapun data PDRB, pengangguran, dan tingkat kemiskinan diunduh dari situs BPS.
Tiga jenis variabel digunakan pada penelitian ini. Pertama, variabel prediktor yaitu TKD (Dana Transfer ke Daerah, merupakan nilai agregat DAU, DAK, DBH, dan Dana Desa), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kedua, variabel respon yaitu TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan TIMIS (Tingkat Kemiskinan, yaitu Persentase Penduduk Miskin). Terakhir, variabel mediator yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
Hubungan ketiga variabel diformulasikan ke dalam model penelitian di bawah. Estimasi model dilakukan dengan path analysis menggunakan Eviews 12 dengan tiga persamaan sub struktural.
Estimasi data panel dilakukan pada tiga persamaan sub struktural. Persamaan sub struktural 1 mengukur pengaruh TKD, PAD, dan KUR terhadap PDRB. Uji Chow dan Hausman menghasilkan model terpilih Fixed Effect (FEM). Persamaan sub struktural 2 mengukur pengaruh PDRB, TKD, PAD, dan KUR terhadap TPT. Hasil uji Chow dan Hausman menghasilkan model FEM. Persamaan sub struktural 3 mengukur pengaruh PDRB, TKD, PAD, dan KUR terhadap TIMIS. Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier menghasilkan model terpilih Random Effect (REM).
Pada tahap akhir dilakukan uji Sobel untuk mengukur hubungan tidak langsung variabel prediktor dengan variabel respon melalui variabel mediasi (PDRB). Uji Sobel dilakukan menggunakan kalkulator online yang menyediakan fitur pengetesan Sobel, yaitu:http://quantpsy.org/sobel/ sobel.htm. Hasil uji Sobel sebagai berikut:
Hasil uji pengaruh tidak langsung TKD terhadap TPT dan TIMIS melalui PDRB belum dapat membuktikan teori FGT bahwa di dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemda berusaha memaksimalkan kesejahteraan rakyat di daerah. Hasil ini mendukung temuan Ali & Ningsih (2021) yang mencatat pengaruh tidak signifikan DAU (TKD) terhadap kemiskinan di Pemkot Metro Lampung.
Hasil uji pengaruh tidak langsung PAD terhadap TPT dan TIMIS melalui mediasi PDRB belum membuktikan teori SGT bahwa pemda menetapkan policy dan aktif menggali sumber pendapatan sendiri guna mendukung perekonomian daerah. Hasil ini sesuai dengan temuan Manek & Badrudin (2016) yang melaporkan dana perimbangan (TKD) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di NTT.
Sebaliknya, Al-Khawarizmi et al. (2021) melaporkan pengaruh langsung dan tidak langsung PAD terhadap kemiskinan.
Uji Sobel pada pengaruh KUR terhadap TIMIS melalui mediasi PDRB dilakukan untuk mengetahui hubungan tidak langsung penyaluran KUR terhadap tingkat kemiskinan dengan mediasi PDRB di NTT. Hasil uji membuktikan secara tidak langsung dana KUR melalui PDRB berpengaruh negatif pada kemiskinan. Artinya, semakin besar (kecil) dana KUR yang disalurkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan menurunkan (menaikan) kemiskinan.
Pengaruh KUR terhadap tingkat kemiskinan melalui mediasi PDRB di sini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam upaya memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah NTT melalui inklusi keuangan. Penetrasi UMKM yang semakin baik atas program bantuan pembiayaan pemerintah telah mampu memberikan hasil yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan Maslikhah (2021), namun sedikit berbeda dalam pemilihan proxy kesejahteraan. Hasil ini mendukung temuan Syam & Musfira (2021) dengan peningkatan pendapatan sebagai proxy kemiskinan.
Kesimpulan Dalam hubungannya dengan PDRB di wilayah NTT, TKD, PAD, dan KUR tidak berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana tersebut belum terlihat dampaknya pada perekonomian kawasan NTT. Faktor misalokasi dana dimungkinkan jadi penyebabnya, bahwa porsi terbesar PAD dan TKD belum dialokasikan pada program/kegiatan belanja yang memberikan nilai tambah lebih bagi perekonomian. Faktor lain yang dapat menjadi penyebab dapat ditinjau dari teori fiscal federalism, yaitu akuntabilitas pemda yang belum terjaga. Pemda yang belum optimal menggali sumber pendapatan sendiri (PAD) cenderung bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan akhirnya jumlah dana yang beredar di wilayah tersebut kecil sehingga belum terasa dampaknya dalam kegiatan ekonomi daerah.
Hubungan KUR dengan TIMIS melalui mediasi PDRB menunjukkan Ha diterima dengan nilai t-statistic bertanda minus. Artinya pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh tidak langsung KUR terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin besar (kecil) dana KUR yang disalurkan akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan menurunkan (menaikan) tingkat kemiskinan. Hasil ini bisa mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam upaya memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah NTT melalui inklusi keuangan.
Artikel ini telah tayang di e-Majalah PADAR edisi Bulan Agustus 2024 dengan judul "Seberapa Jauh PAD, TKD, dan KUR Berpengaruh Pada Kesejahteraan Masyarakat?".