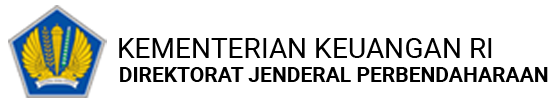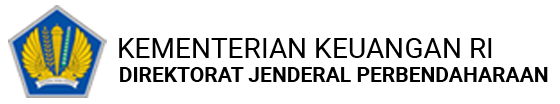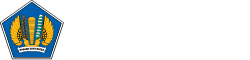Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tanggal 6 Januari 2025 yang dipimpin oleh Mendagri, Badan Pangan Nasional secara ringkas menyampaikan sosialisasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Merespon penyampaian tersebut, Mendagri memberikan komentar penting, di antaranya, "Kalau kita bisa mengajak masyarakat kita untuk tidak hanya bergantung kepada beras, maka sebetulnya kita bisa mengurangi demand atau permintaan untuk suplai beras termasuk mengimpor." Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan tantangan lingkungan.
Perpres Nomor 81 Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pangan nasional. Peraturan ini dimaksudkan untuk mempercepat penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, sehingga tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, tetapi juga memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Dengan memprioritaskan pangan lokal, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat diperkuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta kekayaan alam dan budaya dapat dilestarikan.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan ketersediaan pangan lokal dalam jumlah memadai dengan kualitas yang memenuhi standar konsumsi sehat. Selain itu, pemerintah ingin memperluas akses masyarakat terhadap pangan lokal yang harganya terjangkau. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pemanfaatan pangan lokal untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, sesuai pola pangan bergizi seimbang. Lebih lanjut, kebijakan ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor pangan lokal, dengan memberikan akses pada teknologi, pendanaan, pasar, dan dukungan kebijakan yang relevan.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perpres ini menggariskan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penguatan kebijakan yang mendukung pengembangan pangan lokal, seperti insentif bagi pelaku usaha dan optimalisasi penggunaan dana desa. Program ini juga menekankan pentingnya produksi dan konsumsi pangan lokal dengan memanfaatkan teknologi modern. Selain itu, pengelolaan lahan yang lebih optimal menjadi salah satu prioritas, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekolah untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Pemerintah juga berupaya mengembangkan kapasitas UMKM melalui pendampingan serta pelatihan yang fokus pada peningkatan mutu produk dan akses pasar. Di sisi lain, rantai pasok produk pangan lokal dirancang untuk lebih efisien guna memperluas jangkauan distribusi.
Peran Pemerintah Daerah
Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah. Dengan memastikan rencana tersebut terintegrasi dengan kebutuhan dan potensi lokal, pemerintah daerah dapat mengarahkan kebijakan ini agar berjalan efektif. Dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program percepatan penganekaragaman pangan, seperti pengembangan kebun pangan desa dan penguatan usaha kecil berbasis pangan lokal.
Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam memfasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pangan lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian alat produksi yang dibutuhkan. Hal ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar.
Selain itu, pemda diharapkan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan lokal. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran dan pemberdayaan komunitas lokal, sehingga konsumsi pangan lokal tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat.
Dalam hal ini, pemda perlu melakukan pemetaan potensi lokal secara menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber daya yang dapat dimaksimalkan sebagai produk pangan unggulan. Kolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat lokal perlu ditingkatkan guna mempercepat realisasi program percepatan penganekaragaman pangan. Teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung distribusi dan pemasaran produk pangan lokal, terutama melalui platform daring yang menghubungkan produsen dengan konsumen.
Edukasi dan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, dan media lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal. Pemerintah juga perlu mendorong akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, baik melalui program kredit usaha rakyat maupun insentif lainnya.
Dengan strategi yang beragam dan terintegrasi, konsumsi pangan lokal dapat meningkat secara signifikan. Kampanye ini bukan hanya soal mengganti konsumsi beras, tetapi juga tentang menciptakan budaya baru yang menghargai kekayaan alam dan kearifan lokal. Ketika masyarakat terbiasa dengan pola konsumsi yang lebih beragam, hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani, pelaku UMKM, dan pengusaha di sektor pangan lokal.
Optimalisasi Penggunaan Dana Desa
Penggunaan dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan, yang diatur dalam Permendesa dengan alokasi minimal 20%, adalah peluang besar untuk memperkuat program percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal. Namun, optimalisasi penggunaan dana desa termasuk alokasi dana desa (ADD) memerlukan strategi yang jelas, efektif, dan berbasis kebutuhan spesifik setiap desa.
Pertama, pemerintah daerah perlu mendorong penyusunan rencana kerja pemerintah desa yang memasukkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Setiap desa harus didampingi untuk mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan, seperti lahan pekarangan, kawasan pertanian, atau potensi perikanan. Pendekatan berbasis potensi ini memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Kedua, dana desa dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pertanian kecil yang berkelanjutan. Pembangunan irigasi sederhana, rumah pengolahan hasil tani, atau gudang penyimpanan produk pangan lokal adalah contoh konkret yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian desa. Infrastruktur ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas petani tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan lokal di desa tersebut.
Ketiga, desa juga dapat mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan pendampingan bagi petani, nelayan, atau pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor pangan. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan teknologi pertanian modern, pengolahan hasil pangan menjadi produk bernilai tambah, hingga strategi pemasaran yang inovatif. Pendampingan semacam ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi desa dari sektor pangan.
Keempat, untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan, dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk membentuk koperasi pangan desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang fokus pada pengelolaan pangan lokal. Koperasi atau BUMDes ini dapat berperan sebagai pusat distribusi hasil pangan lokal, sekaligus menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas. Dengan cara ini, nilai ekonomi dari hasil pangan desa dapat dimaksimalkan, sekaligus memperkuat posisi tawar petani atau nelayan lokal.
Kelima, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa dana desa digunakan untuk mendukung program diversifikasi pangan. Misalnya, desa yang memiliki lahan pekarangan luas dapat diarahkan untuk mengembangkan tanaman alternatif seperti singkong, jagung, atau sagu. Desa yang berada di wilayah pesisir dapat memanfaatkan dana desa untuk program budidaya perikanan skala kecil atau pengembangan produk berbasis ikan lokal. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras dan meningkatkan variasi pangan yang lebih sehat dan bergizi.
Keenam, pemerintah daerah dapat memfasilitasi penggunaan dana desa untuk pengadaan alat dan sarana produksi pertanian yang ramah lingkungan, seperti alat pengolahan pupuk organik atau teknologi hemat air. Pengadaan ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini akan memperkuat ketahanan pangan desa tanpa merusak ekosistem setempat.
Ketujuh, untuk memastikan bahwa alokasi 20% dana desa benar-benar efektif, monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting. Pemerintah daerah dapat membantu desa menyusun mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel terkait penggunaan dana tersebut. Laporan ini tidak hanya mencakup data keuangan, tetapi juga capaian program, dampaknya terhadap ketahanan pangan, dan kendala yang dihadapi. Evaluasi yang konsisten memungkinkan pemerintah untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan dan berbasis data.
Kedelapan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa juga perlu diperkuat untuk mendukung optimalisasi penggunaan dana ini. Pemerintah daerah dapat menyediakan tim pendamping desa yang ahli di bidang pangan dan agribisnis untuk membantu desa merancang dan melaksanakan program ketahanan pangan. Pendampingan ini penting agar desa tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban alokasi dana, tetapi juga mampu menghasilkan program-program yang inovatif dan berdampak besar bagi masyarakat.
Dengan strategi yang terencana dan pelaksanaan yang terarah, dana desa termasuk ADD dapat menjadi penggerak utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Program ini tidak hanya memperkuat kapasitas lokal untuk memproduksi pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar wilayah. Optimalisasi penggunaan dana desa adalah salah satu kunci untuk mewujudkan visi besar Perpres Nomor 81 Tahun 2024.
***
Penulis:
Sigid Mulyadi, Kepala KPPN Tanjung
Artikel tersebut telah terbit di Koran Radar Banjarmasin, 9 Januari 2025.