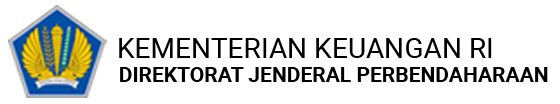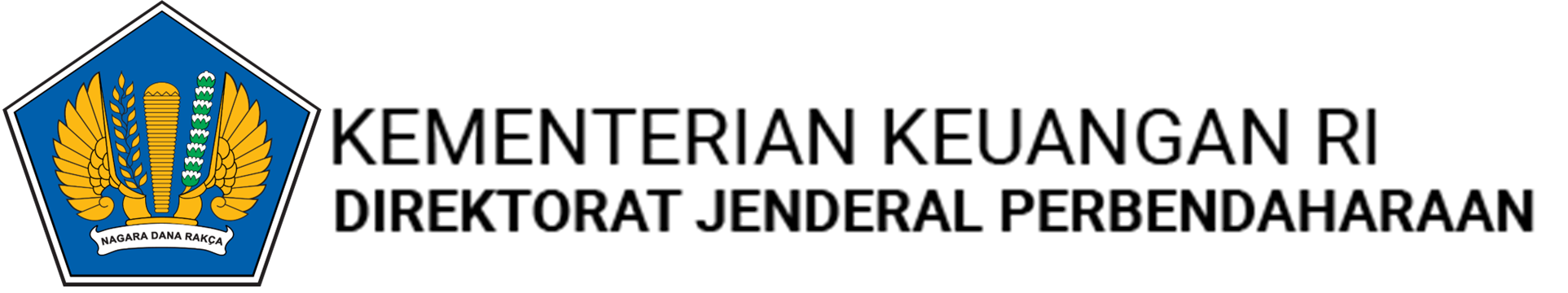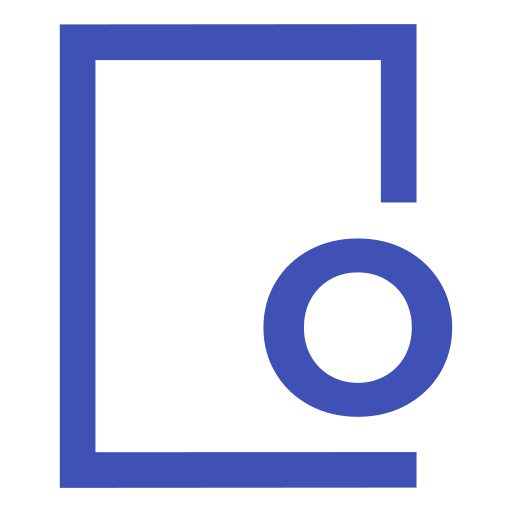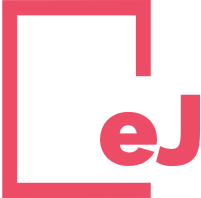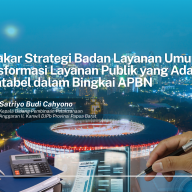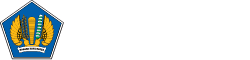Oleh: Rina Karlina, Analis Kebijakan Fiskal pada Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Amalia, pelaksana pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, kami berdua pergi ke daerah Parung Panjang. Tujuan kami adalah untuk melakukan survei lapangan kegiatan komunitas Women Islamic Studies Hub (WISH) Kementerian Keuangan yang dilakukan pada akhir Juni 2025. Kegiatannya meliputi community development berupa keluarga binaan prasejahtera yang berkolaborasi dengan Britania Sari, salah seorang tokoh inspiratif ketahanan pangan di Indonesia. Kami menggunakan moda transportasi KRL Rangkasbitung, kemudian dilanjutkan dengan moda transportasi daring. Perjalanan dari Stasiun Pondok Ranji lebih kurang sekitar 1 jam 15 menit sehingga kami tiba di rumah tujuan sekitar pukul 09.15.
Kami disambut dengan hangat di rumah Mbak Britania yang bernuansa homey. Ditambah lagi dengan rak-rak buku yang berjejer di ruang tamunya, membuat kami merasa semakin nyaman. Kondisi lingkungan di sekitar rumah pun asri karena masih banyak tanaman hijau. Karena Mbak Britania ada jadwal mengajar pukul 11, kami langsung membuka obrolan dengan menanyakan dan mendiskusikan pengalaman personal, kehidupan warga sekitar, hingga proyek-proyek kebaikan yang dilakukan beliau.
Diskusi yang paling membuat hati meleleh adalah terkait kondisi keluarga prasejahtera di lingkungan tersebut. Di sana terdapat sekitar 20 keluarga prasejahtera pendatang yang tidak memiliki rumah. Mereka akhirnya meminta izin untuk menempati rumah-rumah kosong di lingkungan tersebut kepada pemilik rumahnya yang menetap di daerah lain. Hal ini tentu saja sangat berisiko karena sewaktu-waktu sang pemilik rumah dapat mengambil kembali hak hunian atas rumah tersebut dan seketika keluarga prasejahtera tersebut tidak memiliki tempat bernaung lagi.
Mereka juga tidak memiliki pekerjaan yang layak dan memadai (decent job) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Saat diberikan bantuan modal, mereka tidak berani mengambil dalam jumlah besar dengan kekhawatiran tidak dapat menyerapnya karena kapasitas produksi yang terbatas.
Di sisi lain, dengan permodalan yang hanya berkisar antara Rp100.000,00 - Rp200.000,00, keuntungan yang didapat per harinya maksimal hanya sebesar Rp30.000,00. Nominal sebesar itu pun diperoleh jika barang dagangannya habis. Hal tersebut tentunya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga di beberapa kesempatan tidak ada makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh keluarga.
Tantangan yang dihadapi pun tidak hanya berhenti sampai di situ. Permasalahan lingkungan seperti sanitasi, gizi buruk, kerentanan sosial, dan masalah lainnya juga turut menyertai kehidupan keluarga prasejahtera di lingkungan tersebut. Di salah satu rumah warga yang kami kunjungi, airnya keruh dan sedikit berbau. Karena ketidakmampuan untuk membayar tagihan, beberapa rumah warga prasejahtera tidak tersambung dengan air PAM dan listrik.
Kasus stunting juga kerap ditemui yang bahkan berujung pada kematian karena tidak tertangani. Menyedihkannya, kasus pencurian pun terjadi di antara keluarga prasejahtera tersebut. Kondisi ini diperparah lagi karena mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang menunjukkan sebagai warga daerah tersebut. Dengan demikian, mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari Pemda setempat.
Mari kita sandingkan konsep capability approach (CA) dari Amartya Sen dengan permasalahan yang dihadapi keluarga prasejahtera. Konsep CA merupakan awal dari perluasan konsep kemiskinan moneter menuju konsep kemiskinan multidimensi. Dalam konsep ini, Amartya Sen menyampaikan bahwa alih-alih menjadikan kesejahteraan materi sebagai tujuan akhir dari pembangunan, pembangunan seharusnya dilihat sebagai suatu proses untuk memperluas kebebasan seseorang dalam menikmati dan mencapai sesuatu hal.
Kesejahteraan materi sebenarnya justru menjadi sebuah sarana dalam mencapai dan menikmati kebebasan atas hal lain tersebut atau dapat dikatakan sebagai fungsi-fungsi kehidupan yang dianggap berharga oleh seseorang. Kebebasan untuk meraih dan menikmati fungsi-fungsi tersebut ditentukan oleh kapabilitas atau kemampuan seseorang.
Dalam konteks CA, keluarga prasejahtera tentunya tidak memiliki kapabilitas yang cukup. Selain tidak memiliki pendapatan memadai, mereka juga kekurangan kemampuan substantif seperti untuk makan layak, hidup sehat, dan bahkan mendapatkan rasa aman. Oleh karena itu, perbaikan kondisi keluarga prasejahtera ini tidak dapat semata-mata dilakukan hanya dengan peningkatan kapasitas finansial. Kita perlu melibatkan aspek lain juga seperti kesehatan dan hubungan sosial-lingkungan.
Pendampingan dan monitoring yang intensif dalam proses pembimbingan dan peningkatan kapabilitas masyarakat juga sangat diperlukan. Kita juga tidak bisa berharap bahwa ini adalah proses yang instan karena penguatan kapabilitas memerlukan waktu yang tidak sedikit.
Sebagai contoh, mari kita lihat bersama mengenai pemberian bantuan modal kepada keluarga prasejahtera yang sakit-sakitan dan tidak memiliki kendaraan. Pada kondisi tersebut, mereka sebenarnya masih kesulitan untuk tetap dapat makan setiap harinya. Keuntungan hasil penjualan mereka pun kadang tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk melakukan usaha.
Akibatnya, pemberian bantuan modal pun akan teralihkan fungsinya dan terkadang menjadi tidak efektif dan efisien karena tergerus oleh kebutuhan makan sehari-hari. Simpulan logis dari kasus mini tersebut secara sederhana mengungkapkan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari pemenuhan hak dasar dan penguatan kapasitas, bukan hanya sekadar bantuan sesaat.
Mbak Britania sebagai praktisi permakultur berupaya menjadikan kebun sebagai perisai ketahanan pangan masyarakat di lingkungan tersebut. Ia mengajarkan tata cara berkebun dan beternak di pekarangan rumah yang relatif terbatas sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pangan harian. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan tekun.
Mbak Britania mengajari masyarakat yang membutuhkan dari awal dan mendampingi hingga mereka sedikit demi sedikit mulai bisa berdiri sendiri. Tak terbatas di situ, ia juga kerap terlibat dalam penanganan masalah kesehatan pada 20 keluarga miskin paling rentan di wilayah tersebut. Misalnya membantu mengurus tes mantoux dan vaksin untuk keluarga carrier tuberkulosis, serta penggalangan dana untuk anak dengan gizi buruk. Setiap hari, ia juga secara rutin mengunjungi rumah keluarga prasejahtera untuk menanyakan kondisi, mengevaluasi kebunnya, dan berdiskusi.
Dari kisah tersebut, kami menjadi tersadar bahwa terkadang kita harus keluar dari ”bubbles” keseharian yang dijalani. Masih terdapat kelompok masyarakat yang jauh dari kesan nyaman, bahkan pekerjaan pun mereka sulit dapatkan, hanya untuk memenuhi kebutuhan piring harian. Oleh karena itu, kami di WISH Kemenkeu memutuskan untuk mengawali langkah dan membentangkan sayap keluar dari “jalur” yang biasanya, demi mengambil peran kemanusiaan bersama Britania Sari, meski sekecil apa pun peran itu. Semoga kegiatan community development berupa Keluarga Binaan yang akan dilakukan oleh Komunitas WISH pada bulan Juni 2025 dapat menjadi inspirasi dalam menapaki langkah-langkah berikutnya untuk dukungan yang lebih luas.
"Anak muda boleh pandai beretorika, tetapi juga harus sadar untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita." (Muhammad Hatta – Wakil Presiden RI, 1945-1956).
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.