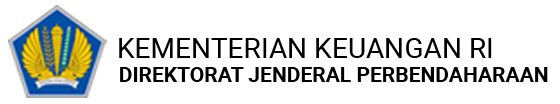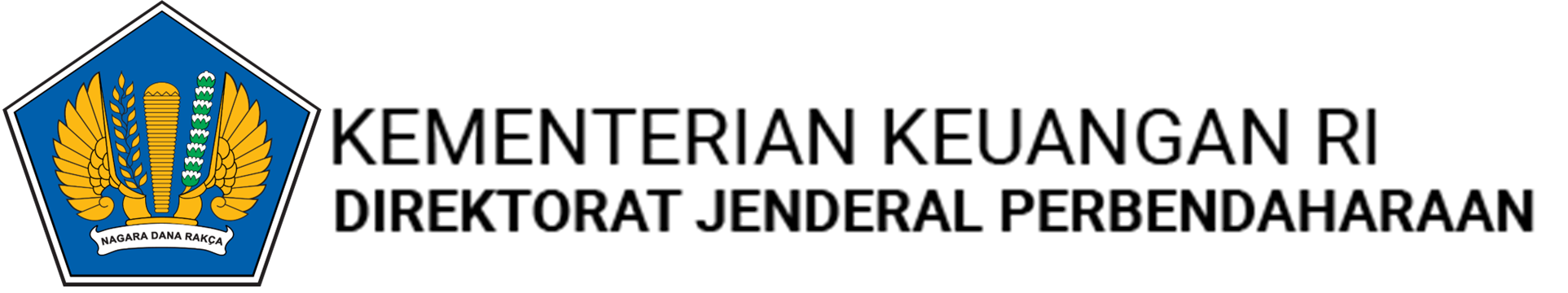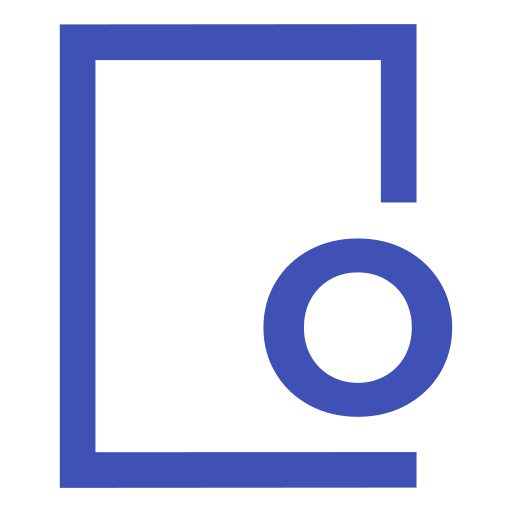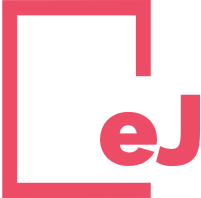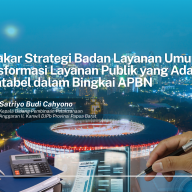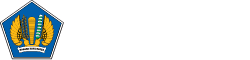Oleh: Joshua Harris Pardamean Samosir, Subbagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian adalah melalui government expenditure. Government expenditure pada prosesnya tidak terlepas dari teknis pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Teknis pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya menjadi bagian yang perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan PBJ, baik instansi pemerintah maupun penyedia memiliki perikatan hukum yang lahir dari kontrak PBJ. Kontrak PBJ menjadi salah satu bagian penting yang sangat memengaruhi terlaksananya proses PBJ.
Kontrak secara umum diatur didalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berberbunyi, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Adapun mengenai PBJ diatur lebih khusus pada Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bahwa “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Penyedia atau pelaksana swakelola.”
Berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat kekhususan pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah jika dibandingkan dengan kontrak secara umum. Kontrak pada umumnya terkait dengan ikatan antarorang (natuurlijke persoon), antarperusahaan (Rechts person), maupun orang dan perusahaan. Sedangkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak yang terikat dalam kontrak adalah penyedia/pelaksana swakelola dengan PA/KPA/PPK. Ketentuan di dalam kontrak PBJ tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, peraturan terkait lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga konsekuensi hukum yang terjadi tentunya akan berbeda dengan kontrak pada umumnya.
Konsekuensi hukum yang berbeda akan menyebabkan risiko hukum yang berbeda. Dalam PBJ terdapat risiko-risiko hukum pada tahap perancangan kontrak PBJ apabila tidak disusun secara cermat, di antaranya risiko kerugian negara, terjadinya wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), maladministrasi, risiko kontrak batal demi hukum atau dapat dibatalkan, penyedia tidak memiliki perizinan yang memadai dalam menjalankan usaha, sengketa hukum antara penyedia dengan subkontraktor, harga kontrak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan risiko lainnya.
Risiko hukum tersebut dapat dihindari apabila para pihak yang terikat dalam kontrak dapat merancang kontrak PBJ dengan cermat, sehingga menghindari risiko-risiko hukum yang dapat terjadi. Dalam merancang kontrak, para pihak dalam hal ini PPK yang memiliki tugas untuk menetapkan rancangan kontrak berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan penyedia perlu memperhatikan beberapa aspek krusial dalam perancangan Kontrak PBJ. Pada tulisan ini, penulis membatasi pembahasan hanya terkait kontrak PBJ antara PPK dengan penyedia.
Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan di dalam kontrak PBJ. Pertama, prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak PBJ pemerintah. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam perancangan kontrak PBJ, yaitu prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip keterkaitan hukum publik dan privat, dan prinsip PBJ pemerintah. Legal protection tidak hanya melihat dari aturan, tetapi wajib memenuhi prinsip yang akan diterapkan dalam kontrak PBJ. Pada penerapan prinsip pengelolaan keuangan negara, apabila jangka waktu kontrak pengadaan lebih dari satu tahun anggaran, maka kontrak PBJ tersebut disebut dengan kontrak tahun jamak, yang PPK wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PA/Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana yang diubah dengan PMK 93/PMK.02/2020 Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan asas tahunan yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
Penerapan prinsip keterkaitan hukum publik dan privat, mengutip pendapat dari Prof. Yohanes Sogar Simamora, dkk. dalam tulisannya “Karakteristik Kontrak Pemerintah dan Problematika Penegakan Hukumnya”, kontrak yang salah satu pihaknya melibatkan pemerintah sejatinya tunduk pada dua rezim hukum yang berbeda, yakni hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata). Hal ini karena dalam melakukan kontrak yang seharusnya tunduk pada hukum privat, pemerintah tidak dapat melepaskan kedudukannya sebagai badan hukum publik yang tunduk pada hukum publik. Hal inilah yang menyebabkan kontrak pemerintah memiliki karakter hibrida (hybrid).
Selanjutnya adalah penerapan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Kedua, terkait dengan subjek hukum dalam kontrak PBJ. Pemahaman yang mendalam mengenai subjek hukum dapat menghindarkan para pihak dari risiko hukum, karena pemahaman tersebut dapat memberikan penilaian apakah subjek hukum sebagaimana dimaksud cakap hukum atau tidak. Ketika subjek hukum dalam kontrak tidak cakap maka terdapat potensi kontrak bisa dibatalkan. Hal ini diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat sah dari kontrak terdiri dari (1) kesepakatan, (2) kecakapan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sehingga ketika tidak terpenuhi, kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, tidak dapat terpenuhinya syarat objektif menyebabkan kontrak batal demi hukum.
Pengertian subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Orang sebagai subjek hukum dibedakan dalam dua pengertian, yaitu natuurlijke persoon atau menselijk persoon yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan rechtspersoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta. Badan hukum (rechtspersoon) dibedakan dalam dua macam yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat (Kansil,1995).
Sehubungan dengan subjek badan hukum publik, pada Pasal 1 Angka 10 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, disebutkan bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Dalam melakukan penelitian terhadap subjek kontrak, perlu diperhatikan keabsahan PPK dalam melakukan penandatanganan kontrak berdasarkan pada surat keputusan dari KPA tentang penetapan PPK. Selain itu perlu juga dimitigasi apabila terdapat mutasi atau pensiun pegawai sehingga PPK yang akan menandatangani kontrak cakap secara hukum untuk mewakili badan hukum publik terkait.
Terkait dengan subjek badan hukum privat, penyedia dalam hal ini dapat berupa manusia/orang maupun badan privat. Bentuk badan privat yang telah diatur dalam perundang-undangan dibagi menjadi perusahaan badan hukum dan bukan badan hukum. Perusahaan bukan badan hukum terdiri atas Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Perdata. Pada Firma, organ yang berhak menandatangani kontrak adalah setiap sekutu dalam Firma (Pasal 17 KUHD), pada CV yang berhak untuk menandatangani kontrak adalah sekutu aktif/komplementer (Pasal 19 KUHD dan Pasal 1 ayat (4) Permenkumham 17/2018), sedangkan pada persekutuan perdata yang berhak menandatangani kontrak adalah masing-masing sekutu mewakili dirinya sendiri terhadap pihak ketiga, kecuali salah satu/lebih sekutu dikuasakan untuk mewakili persekutuan perdata (Pasal 1642 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 3 Permenkumham 17/2018).
Selanjutnya, PPK juga perlu menelaah terkait dokumen akta pendirian/perubahan Firma, CV, dan Persekutuan Perdata. Pastikan nama pihak yang mewakili didalam kontrak telah terdapat di dalam akta pendirian/perubahan tersebut dan memiliki kecakapan secara hukum untuk menandatangani dan terikat dalam kontrak. Apabila pihak yang mewakili dalam kontrak tidak tercantum di dalam akta, maka pihak tersebut wajib untuk mendapatkan surat kuasa dari pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/perubahan untuk menandatangani perjanjian. Selanjutnya dokumen akta pendirian tersebut wajib dilengkapi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Apabila terjadi perubahan akta, maka akta perubahan juga harus dilengkapi dengan SKT dari Kemenkumham. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata)
Sementara itu, untuk perusahaan berbadan hukum, terdiri atas Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. Pada PT, organ yang berhak untuk menandatangani kontrak adalah direksi (Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), pada Yayasan yang berhak menandatangani adalah pengurus (Pasal 35 UU ayat (1) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), dan pada Koperasi yang berhak menandatangani juga pengurus (Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian). PPK juga perlu untuk memeriksa apakah pihak yang mewakili badan hukum telah tercantum identitasnya di dalam akta badan hukum sebagaimana dimaksud, dan dapat secara sah mewakili badan hukum untuk menandatangani dokumen perjanjian. Apabila pihak yang mewakili badan hukum dalam perjanjian tidak tercantum di dalam akta badan hukum, maka pihak tersebut wajib untuk mendapatkan surat kuasa dari pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/perubahan untuk menandatangani perjanjian.
Dalam melakukan pengikatan perjanjian dengan perusahaan berbadan hukum, PPK perlu untuk memeriksa secara rinci mengenai legalitas dari badan hukum tersebut. Legalitas pendirian badan hukum dapat diperiksa dari dokumen akta pendirian/perubahan serta surat keputusan Kemenkumham tentang pengesahan akta pendirian badan hukum dan surat persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Kemenkumham. (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019, dan Permenkumham nomor 2 tahun 2016).
Ketiga, terkait dengan objek dan nature of transaction dalam Kontrak PBJ. Objek kontrak merupakan salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam upaya memetakan risiko suatu perjanjian. Objek Kontrak PBJ secara umum diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Di sini dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya. Setiap jenis objek di dalam kontrak tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, di dalam Buku II KUHPerdata terdapat jenis benda, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Tentunya penerapan ketentuan antara benda bergerak dan tidak bergerak di dalam kontrak akan berbeda. Selanjutnya dapat juga diteliti apakah barang/jasa yang menjadi objek memiliki pengaturan lebih lanjut di suatu aturan pemerintah lain.
Kontrak juga memiliki berbagai jenis transaksi, seperti jual beli barang/jasa, sewa menyewa, dan lain-lain sebagainya. Nature of transaction tersebut menjadi dasar dalam merancang konsep/kerangka hak dan kewajiban di dalam kontrak. Melalui pemahaman atas objek dan nature of transaction di dalam kontrak, PPK dapat melakukan pemetaan risiko terkait proses bisnis transaksi di dalam kontrak serta dapat memitigasi terjadinya ketidakpatuhan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi dan objek barang/jasa tersebut.
Keempat, Pemahaman yuridis dalam perancangan kontrak PBJ mencakup aspek-aspek hukum yang krusial bagi proses pengadaan barang dan jasa. Pertama, legalitas perizinan penyedia, PPK perlu untuk memverifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) serta legalitas usaha lainnya yang dimiliki oleh Penyedia sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ). Kedua, pemahaman tentang jenis kontrak PBJ sesuai Pasal 27 Perpres 12 Tahun 2021 penting untuk menyusun hak dan kewajiban yang tepat sesuai dengan jenis kontrak. Ketiga, keterkaitan kontrak PBJ dengan peraturan lain, memastikan kesesuaian kontrak dengan perundang-undangan terkait. Terakhir, penyelesaian sengketa kontrak PBJ dapat dilakukan di luar pengadilan melalui layanan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi